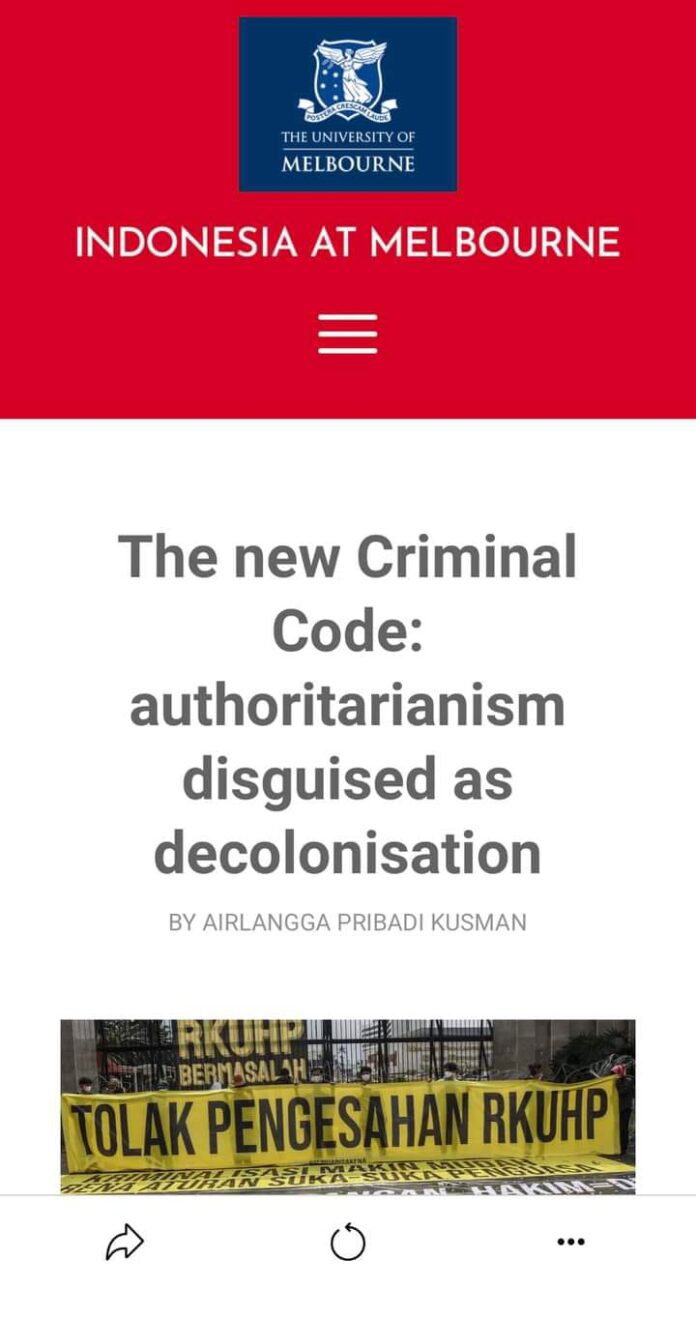Hanya beberapa hari sebelum Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember, orang Indonesia diberi pil pahit untuk ditelan. Pada tanggal 6 Desember, legislatif nasional (DPR) mengesahkan KUHP (KUHP) yang direvisi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej telah mengklaim bahwa kode tersebut merupakan babak baru bagi sistem hukum Indonesia, bahwa ia “mendekolonisasi” sistem peradilan pidana Indonesia, dan menanggapi tuntutan masyarakat akan keadilan.
Tetapi KUHP baru tidak banyak melakukan hal semacam itu. Bahkan, memperkenalkan kembali jenis-jenis ketentuan otoriter yang diwarisi dari kolonialisme Belanda. Ini menunjukkan keberpihakan pada kecenderungan fasis di masyarakat, dan mempercepat regresi demokratis yang telah menjadi ciri khas Indonesia selama 5 hingga 10 tahun terakhir.
Selain artikel yang melarang seks di luar nikah dan hidup bersama yang telah menjadi berita utama global, KUHP baru berisi banyak ketentuan yang secara serius merusak hak-hak sipil. Yang terburuk adalah ketentuan menghina presiden dan lembaga pemerintah, dan yang mencegah penyebaran ide dan konsep yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.
Ketentuan Kolonial
Pasal 218 dan 219 KUHP yang baru menjadikannya pelanggaran untuk menghina presiden dan wakil presiden, dan memperkenalkan hukuman hingga empat tahun penjara atas pelanggaran tersebut.
Sementara itu, Pasal 240 menyatakan bahwa setiap orang yang di depan umum, lisan atau tertulis, menghina pemerintah atau lembaga negara, menghadapi denda atau hukuman penjara hingga 18 bulan.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menjatuhkan ketentuan tentang menghina presiden, memutuskan bahwa mereka tidak sejalan dengan konstitusi demokrasi Indonesia. Tetapi pemerintah telah mengabaikan keputusan Pengadilan, dengan memperdaya dan mengklaim bahwa karena KUHP yang baru membuat pelanggaran “delik aduan” (yaitu, tuduhan hanya dapat dibuat setelah pengaduan oleh individu atau lembaga yang terkena dampak), hal itu berbeda dan dapat dihidupkan kembali.
Pasal ini tidak banyak mengurangi kecenderungan anti-demokrasi yang serius dari ketentuan ini. Daripada mendekolonisasi sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan ini bertindak lebih untuk mengkolonisasi ulang hukum Indonesia.
Pemerintah dan legislatif tampaknya sengaja mengabaikan fakta bahwa salah satu perjuangan utama yang diperjuangkan oleh bapak pendiri Indonesia (Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka) adalah menolak ketentuan kolonial yang longgar tentang ketertiban umum yang sangat mirip dengan Pasal 218, 218 dan 240.
Pidato penting Soekarno melawan kolonialisme, Indonesia Menggugat, disampaikan sebagai bagian dari pembelaannya dalam persidangannya di Landraad kolonial Bandung (Pengadilan Negeri) pada tahun 1930, mencerca apa yang disebut “artikel karet” (haatzai artikelen) yang membatasi kebebasan politik penduduk di Hindia Belanda.
Di negara demokratis yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, pemerintah dan legislatif tidak boleh mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum. Kedaulatan rakyat, sebagaimana diperjuangkan dan diuraikan secara ekstensif oleh pendiri republik Muhammad Hatta, menekankan bahwa otoritas pemerintah didasarkan pada persetujuan rakyat yang diperintah. Baik presiden maupun legislatif tidak memiliki hak atas perlakuan khusus.
Republik dan Demokrasi tidak mengakui presiden sebagai “simbol negara”. Melihat kepala negara sebagai simbol negara adalah sesuatu yang biasanya hanya terjadi pada monarki. Dengan memperkenalkan kembali ketentuan yang melarang menghina presiden dan wakil presiden, pemerintah memulihkan hierarki hukum yang diciptakan oleh pemerintah kolonial.
Seperti yang dicatat oleh mendiang sarjana hukum Indonesia Daniel S Lev, pemerintah kolonial memasukkan budaya patrimonialisme Jawa, dan aristokrasi Jawa yang mendapat manfaat darinya, ke dalam birokrasi kolonial. Aristokrasi Jawa menerima perlakuan khusus – mereka tidak tersentuh oleh hukum pidana kolonial dan diberikan “forum istimewa” di pengadilan kolonial Belanda.
Demokrasi umumnya mengakui perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik. Tapi ini adalah sesuatu yang dinikmati semua warga. Ini bukan hak khusus yang melekat pada posisi atau jabatan publik (pada kenyataannya, di sebagian besar negara demokrasi, pejabat harus menerima lebih banyak kritik daripada warga negara).
Memperkenalkan kembali Pasal 218, 218 dan 240 hanyalah mereplikasi jenis perlakuan khusus yang sebelumnya ditawarkan kepada aristokrasi Jawa oleh penjajah Belanda.
Ada dua implikasi serius dari pengenalan kembali ketentuan tentang menghina presiden dan lembaga negara untuk demokrasi Indonesia.
Pertama, kebebasan politik warga negara membutuhkan jaminan hukum yang kuat. Pengenalan ketentuan ini melemahkan kemampuan warga negara untuk menikmati kebebasan sipil mereka, karena presiden, wakil presiden atau pemimpin lembaga negara pada akhirnya memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah seseorang akan dikriminalisasi untuk kegiatan yang, pada kenyataannya, merupakan hak dasar semua warga negara.
Kedua, artikel tentang menghina presiden dan lembaga negara merusak prinsip-prinsip demokrasi perwakilan, khususnya hubungan antara elit politik dan warga negara, atau masyarakat politik dan sipil. Demokrasi perwakilan dapat mempertahankan dan memperluas demokrasi hanya jika ruang untuk sejumlah pendapat dilindungi secara hukum. Kehadiran sejumlah pendapat di ruang publik yang sehat memberikan kondisi untuk kemajuan kehendak publik yang kuat di ruang publik.
Menempatkan pembatasan pada suara publik, dengan memperkenalkan kembali ketentuan tentang menghina presiden dan lembaga negara, akan mencekik ruang publik. Mereka hanya akan menambah kesenjangan antara elit politik dan warga yang seharusnya mereka wakili.
Momok Marxisme
Sejak Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1965, negara Indonesia telah membangkitkan momok komunisme untuk membenarkan kecenderungan otoriternya. Sejak itu, Marxisme dan komunisme terus disamakan dengan perilaku kriminal.
Pasal 188 KUHP baru mereproduksi momok komunisme dan menentang ideologi nasional, Pancasila. Ini menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mempromosikan komunisme, Marxisme atau pemahaman lain yang melanggar Pancasila menghadapi denda atau hingga empat tahun penjara. Itu juga membuat perbedaan antara Marxisme pada umumnya dan Marxisme sebagai subjek studi, menyatakan bahwa tuduhan tidak dapat diajukan terhadap orang-orang yang mempelajari komunisme untuk tujuan [memajukan] pengetahuan.
Namun, setiap upaya untuk mengkriminalisasi pemikiran melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Selain itu, ketentuan bodoh ini tampaknya akan membedakan antara ajaran Marxis yang disebarluaskan oleh aktivis versus ajaran Marxis yang disebarluaskan di kelas. Di era digital, di mana setiap pembagian antara pendidikan di kelas dan pendidikan di ruang online menjadi semakin tidak berarti, ketentuan ini tampaknya tidak masuk akal.
Ada risiko serius bahwa ketentuan ini akan diterapkan tanpa pandang bulu – setiap aktivitas intelektual yang diliput oleh media dapat ditargetkan jika dianggap terkait dengan Marxisme atau pemahaman “melawan Pancasila”.
Bagaimana pemerintah dapat mengklaim ketentuan tersebut berkontribusi pada dekolonisasi? Siapa pun yang telah mempelajari proses dekolonisasi di Indonesia pasti memahami bahwa bapak pendiri negara itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh ide-ide Marxis dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Teori materialisme historis Marx membantu mereka memahami pola eksploitasi di negara-negara kolonial.
Apakah pemerintah berencana untuk melarang tulisan-tulisan bapak pendiri Indonesia, karya-karya yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan, atas nama “dekolonisasi” KUHP?
Jelas bahwa KUHP baru tidak dimotivasi oleh semangat dekolonisasi atau keinginan untuk menanggapi tuntutan keadilan di masyarakat, seperti yang diklaim pemerintah. Sebaliknya, kode baru mencerminkan kecenderungan otoriter dan opresif terburuk dalam masyarakat Indonesia.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Akbar Faizal, Wakil Menteri Edward Hiariej secara mengejutkan menjelaskan bahwa dia memahami dekolonisasi KUHP Indonesia sebagai tentang menciptakan KUHP Indonesia yang berbeda dengan tatanan hukum di negara-negara Eropa.
Jika itu argumennya – bahwa orang Indonesia secara budaya berbeda dengan orang Eropa dan oleh karena itu memerlukan undang-undang yang berbeda – bagaimana mungkin dia bisa membenarkan Pasal 218, 218 dan 240, yang secara substansial identik dengan hukum opresif yang diterapkan Belanda pada tahap akhir kolonialisme?
Sarjana kritis seperti Edward W Said dan Mahmood Mamdani mengatakan bahwa satu fase dalam proyek imperialisme melibatkan penjajah yang mendefinisikan yang dijajah sebagai “berbeda” dengan mereka yang berada di masyarakat “modern”, dan terus menunjukkan inferioritas mereka kepada orang Eropa sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan.
Dalam mengadopsi KUHP baru ini, negara Indonesia dengan bangga melakukan hal yang sama. Kali ini, kolonialisme bukanlah sesuatu yang didorong ke Indonesia dari luar, tetapi telah disambut – bahkan dirayakan – oleh elit negara itu sendiri.
Warga negara Indonesia tidak boleh tertipu oleh klaim pemerintah tentang dekolonisasi. KUHP baru ini dirancang untuk membunuh demokrasi Indonesia.
© Hak Cipta – Indonesia di Melbourne
Artikel ini bersumber pada laman Indonesia at Melbourne yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2022, telah disetujui untuk diposting dalam bahasa Indonesia di facebook ini untuk kepentingan pendidikan kewargaan.
(ANFPPM)